Mobilitas Perempuan dan Disabilitas di Pesisir: Sebuah Cerita dan Tinjauan dari Kota Makassar
Refleksi di bawah ini ditulis dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional yang jatuh setiap tanggal 8 Maret. Tema tahun ini mengangkat “Invest in Women: Accelerate Progress” dengan harapan dunia dapat menjamin hak-hak perempuan di seluruh lini untuk mencapai perekonomian yang sejahtera dan adil, serta Bumi yang sehat untuk generasi mendatang. Terjaminnya mobilitas perempuan yang aman dan nyaman sudah sepatutnya menjadi perhatian bersama mengingat akses transportasi untuk mobilitas sehari-hari merupakan salah satu penunjang untuk kesempatan mencapai penghidupan dan kesejahteraan yang layak dan berdaya.
Penulis merupakan staf komunikasi untuk program WRI Indonesia terutama di portofolio perkotaan turut mengikuti perjalanan usaha mencapai mobilitas yang rendah karbon dan inklusif dalam Program Kota Masa Depan UK PACT di Kota Makassar dan Surabaya. Di sini, penulis berkesempatan untuk mendengar cerita-cerita mobilitas kota dari ragam pengalaman dan perspektif.
Sepenggal Cerita dari Kota Makassar
Pengalaman penulis sebagai warga Kota Bogor yang menghabiskan banyak waktunya dengan bertransit lintas Jabodetabek cukup nyaman, karena kota-kota ini sudah terfasilitasi akses transportasi publik. Meski demikian, sebagai perempuan penulis kerap mengalami kejadian khusus yang tidak menyenangkan. Pengalaman bermobilitas tersebut yang mendorong perhatian penulis terhadap isu mobilitas yang aman dan nyaman.
Keterlibatan penulis dalam Program UK PACT ini cukup menyadarkan bahwa pengalaman bermobilitas perempuan tidaklah tunggal karena ada banyak faktor dan status lainnya yang turut andil. Tidak terkecuali kota yang penulis tinggali dengan kota pesisir seperti Makassar. Kota Makassar memiliki sejumlah pulau di tengah kota yang dibatasi oleh sungai atau laut sehingga sebagian warganya mengandalkan kapal atau perahu untuk bermobilitas. Beberapa waktu lalu, penulis menyempatkan diri untuk merasakan pengalaman mobilitas ini dengan mengunjungi Pulau Lae-Lae dan Pulau Lakkang, serta bercakap langsung dengan warga tentang pengalamannya.
Pembicaraan seputar mobilitas lintas pulau lebih lanjutnya didapatkan penulis ketika berjumpa dengan kelompok rentan pada kegiatan rutin program, yakni forum multipihak “Tudang Sipulung”. Di sinilah penulis berjumpa dengan Risya, ASN Provinsi Sulawesi Selatan dan anggota Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Makassar; serta Mardiana, warga Pulau Barrang Lompo, dan keduanya sempat membagikan pengalamannya bermobilitas di Kota Makassar.
Kedua narasumber tinggal cukup jauh dari pusat Kota Makassar; Risya bertempat tinggal di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Marros; sementara Mardiana tinggal di Pulau Barrang Lompo. Kedua daerah tersebut membutuhkan kurang lebih satu jam menuju pusat kota. Namun, kiranya perjalanan satu jam ini berbeda dengan pengalaman penulis sebagai perempuan suburban yang memiliki akses ke transportasi umum, seperti KRL, yang terintegrasi dengan layanan pendukung menuju last mile sehingga memudahkan penulis untuk melakukan transit dan bekerja di Ibu Kota.

Menurut Risya kebanyakan teman-temannya cenderung memilih angkutan kota (angkot), yang umumnya warga Kota Makassar sebut sebagai “pete-pete”, untuk bepergian karena harganya yang relatif terjangkau. Sementara itu, Risya sebagai penyandang disabilitas netra merasa lebih nyaman dan aman ketika diantar keluarga atau oleh jasa transportasi online langganan, sehingga sang ojol mau berkompromi menjadi pengemudi offline. Layanan seperti ini turut mendukung Risya memenuhi kebutuhan yang terkait dengan disabilitasnya.
Risya juga berujar bahwa sekalipun ia ingin ataupun harus bepergian menggunakan pete-pete dari Kelurahan Moncongloe, Risya juga akan kesulitan bermobilitas menuju tempat kerjanya di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan karena daerah Moncongloe tidak dilalui transportasi umum. Sisi lain transportasi online adalah harganya yang cenderung melonjak saat musim hujan sehingga cukup memberatkan bagi sebagian disabilitas netra. Terlebih, beberapa rekannya juga harus mengeluarkan biaya lebih untuk menggunakan pendamping sebagai ucapan terima kasih.
Keengganan Risya untuk mengandalkan transportasi umum juga tidak lepas dari faktor sosial budaya serta norma yang beredar di masyarakat, seperti anggapan bahwa perempuan tidak seharusnya menggunakan transportasi umum; dan pengalaman teman-teman perempuannya, baik disabilitas maupun nondisabilitas, yang mengalami pelecehan seksual di angkutan umum. Data CATAHU Komnas Perempuan mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan di ruang publik tahun 2022 mencapai 2.978 kasus. Sementara itu, survei Koalisi Publik Ruang Aman (KPRA) menemukan kasus pelecehan yang dialami perempuan umumnya terjadi di transportasi umum.
Pengalaman bermobilitas menjadi semakin sulit ketika hujan turun. Tidak hanya keterbatasan moda, tergenangnya akses pejalan kaki dan jalanan semakin menyulitkan Risya untuk menavigasi perjalanannya. Bagi ibu rumah tangga seperti Mardiana, curah hujan yang deras tempo hari menyulitkan pertemuannya dengan kerabat dan keluarga terdekat karena risiko ombak laut yang semakin memisahkan Pulau Barrang Lompo dengan Kota Makassar. Kapal motor tradisional yang dikelola warga lokal, beroperasi pada pukul 07.00 dan 11.00 WITA menjadi satu-satunya moda transportasi Mardiana dan warga Pulau Barrang Lompo menuju pusat kota. Dilatarbelakangi oleh keterbatasan ragam pangan di pulau, kapal ini umumnya digunakan penjual sayur untuk membeli kebutuhan pangan di pusat kota.

Mardiana sendiri menggunakan kapal motor tradisional untuk keperluan pertemuan di kota, mengunjungi anak perempuannya yang berkuliah di kota (atau sebaliknya), dan mengantarkan anaknya yang sakit ke rumah sakit di pusat kota. Menurutnya, akses layanan kesehatan di pulau belum sepadan dengan yang ada di pusat kota sehingga demi kebutuhan obat dan penanganan khusus, ia harus menyebrangi laut.
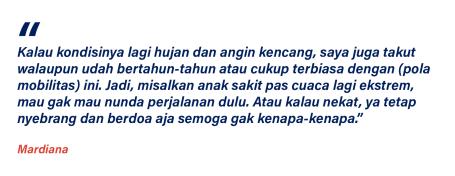
Menilik Keadilan Bermobilitas di Kota
Dalam tinjauan keadilan bermobilitas, mobilitas dilihat tidak terbatas pada transportasi melainkan juga meliputi mobilitas fisik tubuh seseorang yang erat kaitannya dengan konstruksi gender, abilitas, dan seksualitas; rasialisme dan pengelompokan; serta bagaimana semuanya saling berinteraksi dan tumpang tindih (interseksional).
Mobilitas seseorang juga tidak lepas dari pengaruh perubahan iklim dan ketahanan kota; aksesibilitasnya bagi lansia, anak-anak, penyandang disabilitas dan masyarakat miskin; serta nilai dan norma dalam masyarakat yang menyokong peran gender tradisional. Bencana iklim seringkali menghambat mobilitas atau bahkan memaksa seseorang untuk berpindah tempat, yang pada praktiknya tidak dapat dilakukan secara efektif oleh kelompok rentan, seperti perempuan disabilitas dan perempuan yang tinggal di pulau.
Dampak perubahan iklim seperti bencana cuaca ekstrem mempengaruhi aktivitas sehari-hari masyarakat perkotaan, tidak lain adalah mobilitas masyarakat. Dampak tersebut menjadi ancaman khusus bagi kota-kota pesisir mengingat posisinya sebagai garis terdepan ketika menghadapi paparan bencana iklim. Di sektor mobilitas, cuaca ekstrem mengakibatkan terendamnya jalan, permukiman, dan sentra perekonomian akibat limpasan air laut; serta terhambatnya aktivitas masyarakat yang tinggal di pulau-pulau sekitar kota dikarenakan meningkatnya suhu panas berimplikasi terhadap besarnya gelombang air laut, angin kencang, hingga badai.
Kejadian ini yang nampak dialami oleh Mardiana di tengah kondisi belum memadainya pelayanan dasar di pulau, ia harus menuju pusat kota dengan mempertimbangkan risiko menyebrangi laut. Pengalaman serupa juga kami dapatkan saat sempat mewawancarai warga Pulau Lae-Lae meskipun pulau ini tidak sejauh Barrang Lompo. Begitu pun dengan Risya, hambatan mobilitas darat akibat terendamnya jalan semakin menyulitkannya menavigasi kondisi jalan.
Pentingnya Mobilitas Berkelanjutan di Kota Pesisir
Pada tahun 2023, Konsorsium II UK PACT telah melakukan studi Kajian Ketahanan Masyarakat Perkotaan (UCRA) Kawasan Metropolitan Mamminasata1. Beberapa temuannya mengungkapkan Kota Makassar memiliki aksesibilitas transportasi yang kurang memadai sehingga belum mengakomodasi kebutuhan pergerakan masyarakat seperti bekerja dan mengakses layanan dasar. Selain itu, ditemukan bahwa perempuan dan anak muda merupakan kelompok dominan pengguna transportasi umum.
Kota Makassar memiliki sejumlah layanan transportasi umum, seperti pete-Pete yang berjumlah 1.101 unit (2021), Trans Mamminasata berjumlah 200 unit (2021), transportasi online, sewa mobil atau motor dengan tarif Rp250.000–Rp300.000/hari, dll.. Berdasarkan survei tahun 2021 terhadap 400 responden, ditemukan mayoritas pengguna transportasi umum adalah perempuan. Selain itu, mayoritas penggunanya adalah masyarakat berpenghasilan <Rp1.000.000–Rp2.500.000. Dalam suatu forum diskusi, kami mendapati pula bahwa baik perempuan maupun penyandang disabilitas mengandalkan transportasi umum lantaran harganya yang relatif murah. Namun, dikarenakan fasilitas yang kurang memadai, sebagian dari mereka beralih mengandalkan transportasi online atau bergantung pada suami atau anak laki-laki yang relatif memiliki akses terhadap kendaraan roda dua/empat.
Kerentanan Kota Makassar di sektor mobilitas perlu direspons dengan aksi iklim dengan memperbaiki sistem transportasi yang rendah karbon sekaligus membuka kesempatan pembenahan sistem transportasi. Sektor transportasi merupakan penyumbang emisi gas rumah kaca (GRK) terbesar ketiga di Indonesia, yakni 27%. Oleh karenanya, dekarbonisasi sektor transportasi di tingkat subnasional menjadi langkah penting dalam mendukung pencapaian target emisi nol bersih Indonesia tahun 2060.
Aksi iklim ini perlu dibersamai dengan pembenahan sistem transportasi yang terintegrasi dan inklusif, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan lebih optimal dan terciptanya mobilitas yang berkelanjutan. Mobilitas berkelanjutan adalah prinsip pembangunan sistem transportasi yang menjamin pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan suatu masyarakat dan meminimalisasi dampak yang tidak diharapkan dari ketiga sektor tersebut. Pada dasarnya, praktik mobilitas berkelanjutan ini turut sejalan dengan rekomendasi UCRA.

Intervensi yang dilakukan oleh Konsorsium II UK PACT adalah berupaya mewujudkan sistem transportasi Kota Makassar yang andal dengan memperbaiki first mile dan last mile, khususnya di kawasan yang padat penduduk; serta menerapkan penataan kawasan yang terintegrasi. Hal ini akan mendorong mobilitas aktif dengan penyediaan fasilitas pejalan kaki dan pesepeda yang efektif serta memadai.
Sebuah Penutup: Perlunya Solidaritas untuk Mobilitas Kota Inklusif
Penggalan cerita dan tinjauan tersebut menjadi gambaran kecil tentang pengalaman kerentanan perempuan dalam bermobilitas akibat interseksi beragam identitas rentan yang dimilikinya. Baik Risya dan Mardiana tentunya memiliki harapan agar kemajuan kota turut diiringi akses bermobilitas yang inklusif bagi berbagai kelompok rentan di tengah ancaman iklim. Jumlah kapal penyebrangan yang memadai dan dikelola oleh pemerintah, serta tarif yang akomodatif bagi anak-anak atau pelajar menjadi salah satu harapan Mardiana selaku perempuan pulau.
Aspek akomodatif bagi kelompok berkebutuhan khusus juga menjadi harapan Risya. Menurutnya, keberadaan penjaga khusus yang responsif (siap siaga membantu kelompok prioritas dan mampu menyikapi pelecehan) di transportasi umum menjadi aspek keamanan dan kenyamanan bermobilitas bagi kelompok rentan. Melalui kerjakerja advokasi dan/atau pemberdayaan perempuan, Risya dan Mardiana telah mengupayakan berbagai hal yang dapat mendorong perempuan untuk menciptakan ruang publik yang tidak hanya akses, melainkan juga akomodatif terhadap kebutuhan khusus. Ini saatnya, seluruh elemen masyarakat bersama-sama mendorong pengarusutamaan gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam seluruh layanan publik.
1 Mamminasata: Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar